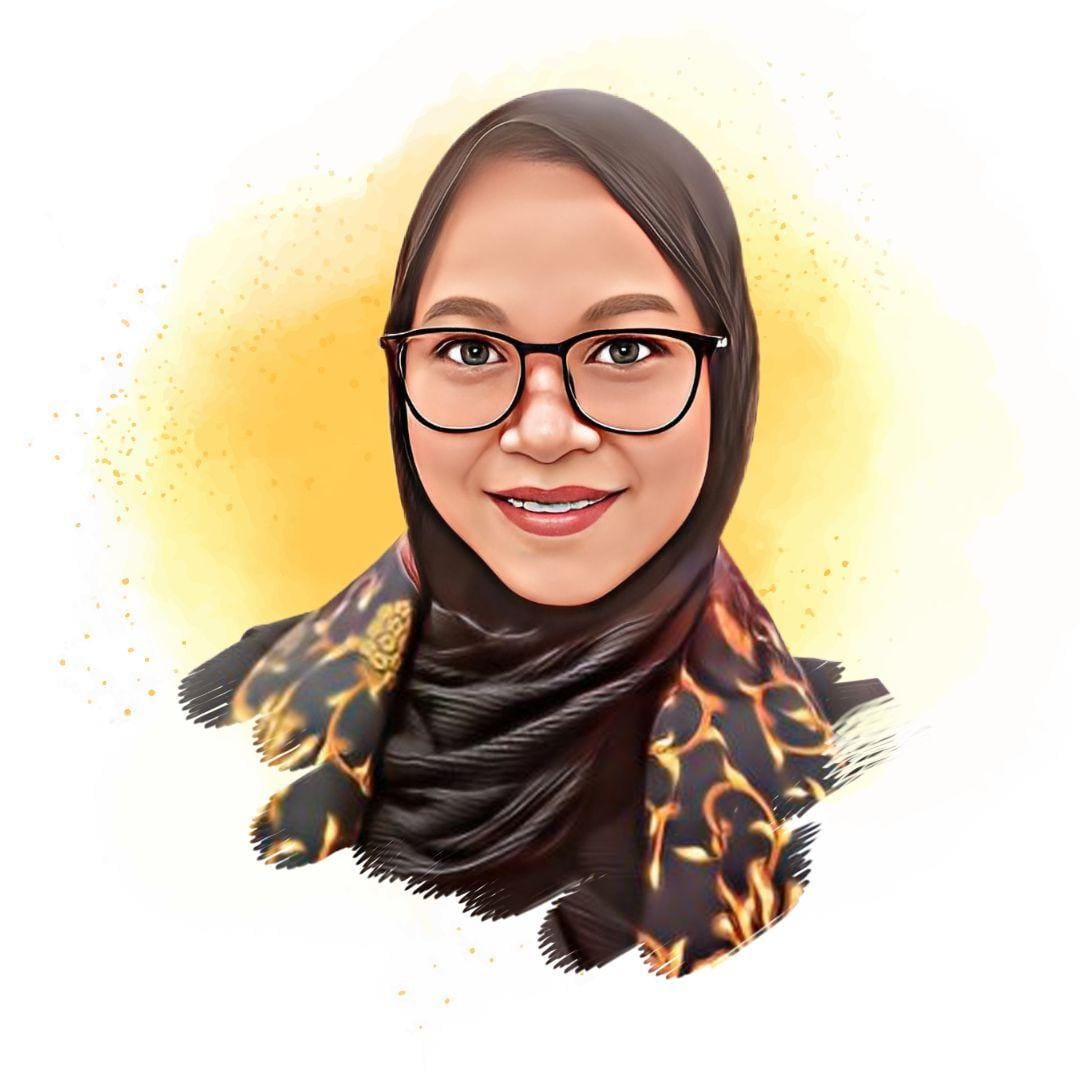Waranggana bersinar di tengah dominasi laki-laki. Mereka adalah subjek aktif dalam struktur harmoni. Di masa lalu, penari-penyanyi ini dikenal sebagai salah satu representasi dari ideologi gender khas perempuan Jawa. Namun, kepercayaan perempuan memudar sejak peristiwa tragis tahun 1998 yang mengubah persepsi mereka terhadap harmoni yang diidamkan dalam masyarakat Jawa.
Inilah fokus utama Nancy I. Cooper dalam memotret waranggana, seperti yang tertulis dalam penelitiannya berjudul “Singing and Silences: Transformations of Power Through Javanese Seduction Scenarios.”
Tumbuh dari Ideologi Gender Khas Jawa
Menurut catatan Nancy I. Cooper, orang Jawa memang memandang perempuan sebagai sosok yang kuat. Namun, dalam praktiknya, perempuan Jawa menunjukkan kekuatan mereka secara tidak langsung. Dengan kata lain, mereka memiliki cara berbeda untuk mengekspresikan kepentingan pribadi sembari menjaga harmoni dan kerja sama dengan laki-laki.
Perempuan mungkin tidak selalu berada di garis depan dalam pengambilan keputusan formal, tetapi mereka memiliki cara tersendiri untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan mereka didengar dan dipertimbangkan. (Titi Surti Nastiti, 2016) Selain itu, perempuan Jawa memiliki peran vital dalam mengelola ekonomi keluarga.
Cooper melihat ciri-ciri ini selama tinggal dalam struktur rumah tangga di Jawa yang berpusat di sekitar istri dan kerabat perempuan. Mereka mengelola rumah tangga, bekerja di ladang, menghasilkan banyak uang (bahkan melebihi pemasukan suami mereka). Ciri umum lainnya adalah perempuan bahkan tidak diharapkan untuk menjadi ‘halus’ atau ‘bermartabat’ dalam struktur sosial yang setara dengan laki-laki.
Kebebasan sosial ini juga tumbuh dalam konteks dunia waranggana. Banyak diantara mereka yang menjadi kontributor utama ekonomi keluarga. Seperti para orang tua mereka yang umumnya adalah petani. Waranggana sebagai representasi perempuan Jawa diharapkan sangat resilience (adaptif dan gigih), pekerja keras, bertanggung jawab dan tentu juga hemat. Citra inilah yang ditampilkan waranggana baik di panggung, rumah, ladang maupun pasar.
Oleh karena itu, nyanyian dan tarian waranggana dianggap mewakili kepercayaan pada kekuatan perempuan yang termanifestasi dalam sosok “Dewi Sri”. (Anik Juwariyah dkk., 2023) Khususnya ditujukan untuk para pekerja perempuan yang menjadi pengikut Dewi. Seorang dewi yang mengatur makanan pokok masyarakat Jawa. Sayangnya, posisi perempuan berubah seiring dengan perubahan sistem agraris masyarakat Jawa dan memudarnya kepercayaan kepada Dewi mereka.
“Skenario Rayuan” Waranggana
Di satu sisi, Cooper juga menegaskan bahwa kekhasan gender perempuan di Jawa dan harmoni yang saling melengkapi ini tidak dapat disamakan dengan pandangan ‘kesetaraan’ modern. Secara jujur, Ia menambahkan bahwa masyarakat Jawa tetap memiliki sistem patriarki yang jelas dalam struktur resminya. Dengan demikian, dalam konteks gender di Jawa hari ini, kita masih mengenal waranggana.
Dalam bahasa Kawi (Jawa Kuno), “Wara” berarti perempuan dan “Anggana” berarti sendiri. Gabungan kedua kata ini mendekati makna “Perempuan yang Mandiri”, “Perempuan yang Tersendiri”, dan “Perempuan yang Istimewa”. (Edi Sedyawati, 1995) Namun, tidak seistimewa namanya, perempuan yang menjadi waranggana seringkali dituduh sebagai “Pelacur” karena suara dan tubuhnya memanjakan banyak mata laki-laki.
Sedangkan seorang waranggana hanya bermain peran, yang disebut Cooper sebagai “Skenario Rayuan,” saat menari dan bernyanyi bersama laki-laki. Tujuannya tidak lain untuk menguji laki-laki dan menjaga nilai mereka dalam konstruksi sosial yang harmonis ini. (Nancy I. Cooper, 2000) Waranggana secara sadar menempatkan diri mereka untuk ‘dirayu dan merayu’ laki-laki.
Laki-laki yang diuji oleh seorang waranggana adalah mereka yang bersedia menari, berbincang, beserta pasangan mereka sendiri. Melalui interaksi ini, waranggana tidak hanya menghibur tetapi juga memperlihatkan keterampilan bersosial yang rumit dengan kemampuan untuk mempengaruhi dinamika sosial. Mereka memastikan keseimbangan sosial, nilai-nilai tradisional tetap hidup dan dihormati.
Secara tidak langsung, seorang waranggana juga menjadi perlambang dari kekuatan dan kecerdasan perempuan dalam struktur patriarki. Sementara berinteraksi dengan laki-laki dalam batas-batas yang ditetapkan oleh masyarakat, mereka tetap memiliki kuasa dan pengaruh yang signifikan. Selain itu, peran mereka dalam “Skenario Rayuan,” mengingatkan bahwa harmoni sosial tidak hanya tentang kepatuhan terhadap norma-norma tetapi juga tentang kemampuan untuk bernegosiasi dan memanipulasi peran yang diberikan kepada mereka.
Dalam setiap tarian dan nyanyiannya, waranggana mengajarkan bahwa kekuatan perempuan dapat ditemukan dalam ketahanan dan adaptasi, serta dalam kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara yang halus dan cerdas. Dengan demikian, waranggana menjadi lebih dari sekadar penghibur; mereka adalah penjaga harmoni, agen perubahan, dan simbol kekuatan perempuan dalam masyarakat Jawa yang terus berkembang.
Harmoni yang Memudar
Harmoni yang dijaga oleh waranggana, khususnya dalam hubungan tanpa konflik yang ditampilkan oleh perempuan dan laki-laki di Jawa, bahkan menjadi dambaan di seluruh negeri. Namun, citra harmoni yang kuat ini terguncang hingga ke intinya ketika sekelompok laki-laki merudapaksa setidaknya 50 perempuan dan anak perempuan di jalanan. Kejadian tragis ini terjadi pada kerusuhan Mei tahun 1998.
Beberapa perempuan diseret dari rumah mereka dalam puncak amukan kerusuhan, penjarahan dan pembakaran yang akhirnya merenggut 1.200 nyawa. Amukan ini menghancurkan ribuan rumah dan bangunan lainnya, mempercepat jatuhnya mantan Presiden Suharto dan pemerintahannya yang represif selama tiga dekade. (Nancy I. Cooper, 2000)
Beberapa orang yang menyaksikan rudapaksa itu melaporkan bahwa ketika beberapa penonton laki-laki bersorak, yang lain mengambil foto (seolah-olah untuk meneror dan mengintimidasi korban lebih lanjut sehingga mereka tidak akan berbicara nanti). Ada yang memaksa pekerja rumah tangga laki-laki untuk merudapaksa majikan mereka (perempuan atau anak perempuan) dengan benda-benda, dan memaksa anggota keluarga untuk menonton tontonan mengerikan itu.
Dari semua kekejaman kerusuhan, banyak perempuan dari kelompok minoritas yang dirudapaksa secara massal. Sejak saat itu, kepercayaan terhadap harmoni mulai memudar karena kekejaman terhadap perempuan dibiarkan merajalela. Pada akhirnya, perempuan menjadi yang paling traumatis dan terdampak jika terjadi kembali peristiwa serupa.
Sebagai antitesis dari konsep rukun, episode menghancurkan dalam sejarah Indonesia itu mengingatkan masyarakat, khususnya di Jawa, akan pentingnya ideologi budaya yang mempromosikan keharmonisan. Namun dengan ironi, perempuan tetap rentan menjadi korban kekerasan meskipun harapan akan kedamaian ditekankan.
Oleh karena itu, setiap perempuan perlu menemukan kekuatannya agar representasinya dalam sosok waranggana yang kuat tidak hanya terdengar sebagai nyanyian sunyi belaka. Sekaligus ini adalah panggilan untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan membangun masyarakat yang lebih adil dan berempati terhadap setiap orang. []
“Out of all wars, which are all started by men, none of them have made life better for mankind. Therefore, women, as the source of love in human society, must take the strength that determines life as their own.” – Nyai Ontosoroh