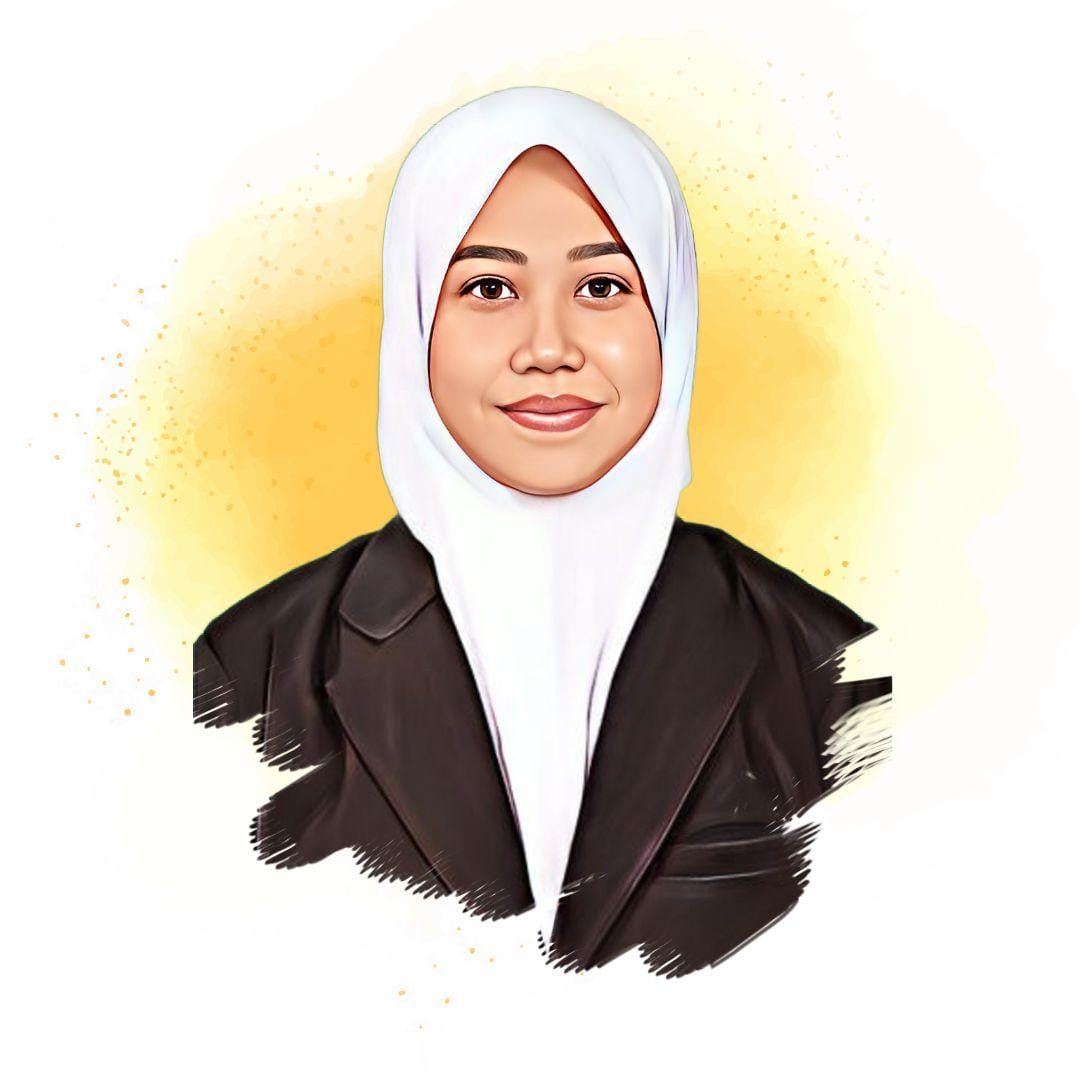Pemerintah Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai kiblat perkembangan budaya. Konsekuensinya, adat lokal diarahkan sejalan dengan ideologi negara. Ideologi ini dijadikan rujukan utama pemerintah Orde Baru mengatur kehidupan masyarakat. Budaya yang sebelumnya merupakan praktik hidup masyarakat bergeser menjadi seni pertunjukan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, pertunjukan tayub merupakan salah satu yang terdampak.
Pada situasi ini, Pancasila hadir sebagai asas tunggal, ia menjadi rujukan dalam mengatur kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Masyarakat dituntun hidup sesuai nilai Pancasila, sebab, titik tekan ada pada posisi Pancasila sebagai pondasi utama bernegara. Dalam kerangka Orde Baru, pemerintah giat mempromosikan Pancasila sebagai payung pemersatu keragaman, segala bentuk organisasi politik, sosial, dan budaya wajib tunduk pada Pancasila. Hal ini menjadi pijakan negara menstrukturkan kebijakan, termasuk kebijakan budaya.
Tepat di titik ini, nyatanya Pancasila bukan sekedar slogan Orde Baru, melainkan ide yang telah ada sejak awal kemerdekaan. Era awal kemerdekaan, Pancasila diletakkan sebagai dasar negara yang menampung berbagai ideologi. Sejak saat itu, konsep Pancasila adalah sebagai prinsip pemersatu bangsa untuk mengatasi konflik politik dan ideologi di Indonesia yang sangat beragam. Sehingga, dirancangnya Pancasila untuk menyatukan perbedaan sudah ada sejak era Soekarno (Greg Acciaioli, 1985).
Akan tetapi, fungsi pemersatu ini tidak berhenti dalam tataran politik, ia turut hadir dalam ranah budaya. Pancasila bekerja sebagai filter, yang menentukan bentuk budaya mana yang layak dipertahankan, dimodifikasi atau dihapuskan. Adat yang hidup dapat diterima sejauh ia tidak bertabrakan dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui kebijakan ini, Pancasila berperan sebagai payung pemersatu sekaligus alat domestikasi, sehingga keragaman tetap bisa ditampilkan namun dengan ruang gerak yang terbatas. Dengan cara ini, kontrol tetap bisa dijalankan.
Pemerintah melakukan kontrol dengan mekanisme desakralisasi. Sebab, sila pertama mengharuskan masyarakat memeluk salah satu agama resmi. Sehingga segala praktik beragama yang tidak sesuai agama resmi secara otomatis menerima kecaman (Philip Yampolsky, 1995). Hal inilah yang menimpa pertunjukan tayub, ia pada mulanya hadir pada pesta yang diadakan dalam ritual pasca panen (Felicia Hughes-Freeland, 1997). Tayub dihadirkan sebab ia lekat dengan ritual kesuburan.
Dalam hal ini, ledhek, yakni penari dalam pertunjukan tayub dianggap memiliki kekuatan penyembuhan. Pada praktiknya, mereka menggunakan bedak wajah untuk melindungi serta menyembuhkan orang serta hewan (Felicia Hughes-Freeland, 2008). Bedak tersebut biasanya akan dioleskan pada bayi atau tali hewan. Tidak sampai di situ, bahkan ciuman dari ledhek dianggap membawa keberuntungan dan kesembuhan (Felicia Hughes-Freeland,1997). Diluar kepercayaan masyarakat terhadap ledhek sebagai pembawa kesembuhan, ia juga menari secara bergantian dengan para pria pada saat pertunjukan.
Kehadiran ledhek inilah yang sebenarnya menimbulkan kecaman. Ia dipandang negatif karena perilaku-perilaku yang dianggap tidak bermoral ketika pentas berlangsung, seperti para tamu yang berkecenderungan ingin merangkul ledhek akibat pengaruh alkohol dan hadirnya saweran. Padahal, di desa-desa Jawa Timur, ada anggapan bagi perempuan desa untuk tidak menari dalam bentuk apapun, apalagi dalam acara sebebas tayuban (Robert W. Hefner, 1987). Kehadiran hasrat dan uang dalam tayuban menempatkan penampilan mereka di luar batas budaya Orde Baru (Felicia Hughes-Freeland, 2008).
Sebab, pemerintah menghendaki perkembangan budaya didasarkan pada Pancasila, yang sering dipromosikan pejabat lokal seperti camat dalam kunjungannya ke desa-desa (Greg Acciaioli, 1985). Tiap kali melakukan kunjungan ke desa, camat selalu menyampaikan serangkaian pidato pada penduduk desa, isi pidatonya berfokus pada tema Pancasila. Acciaioli bahkan menyampaikan, pidato yang disampaikan camat di tiap desa yang ia kunjungi memiliki inti yang sama. Dalam proses ini, unsur agama yang mengacu pada sila pertama menjadi bagian penting untuk memperkuat persatuan nasional.
Dimulai dari camat yang menekankan peran agama sebagai obor penerang jalan kehidupan bagi penduduk, negara melanjutkan pada sistem pengelompokan yang seragam dan terkontrol, di mana negara menentukan wadah resmi untuk keagamaan rakyat. Negara menetapkan seluruh warga negara harus menganut salah satu dari lima agama resmi yang diakui, mematuhi agama berarti afirmasi terhadap usaha nasionalis (Greg Acciaioli, 1985).
Mengutip Atkinson, Acciaioli menerangkan bahwa agama memiliki posisi sangat penting dalam nasionalisme. Negara menjamin kebebasan beragama, namun hanya bagi mereka yang menganut agama resmi, sistem kepercayaan dan ritual adat tidak diakui sebagai agama. Dalam kerangka budaya nasional, agama dipandang sebagai tanda pendidikan, kecanggihan dan kemajuan. Oleh sebab itu, menganut agama resmi dianggap selaras dengan identitas sebagai warga negara.
Selain itu, intervensi pemerintah juga hadir melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), yang fokus mengintervensi kebudayaan daerah di desa-desa. Salah satu tujuan Depdikbud adalah mengendalikan konten moral. Pemerintah menekankan agar seni tidak mendukung aktivitas yang dianggap tidak bermoral, seperti mabuk-mabukan, judi, dan perilaku yang mengindikasikan kebebasan seksual (Philip Yampolsky, 1995). Melihat kategori di atas, tayuban dengan segala kebiasaan di dalamnya sudah pasti menjadi kandidat utama penertiban moral.
Di lain sisi, mengenai posisi ledhek dalam pertunjukan tayub, penilaian negatif terhadap ledhek nampaknya sejalan dengan promosi negara mengenai peran perempuan sebagai ibu dan pengasuh di ranah domestik. Ledhek yang menjalankan unsur supranatural dalam ritual agraris tahunan dipandang sebagai sesuatu yang kuno dan ketinggalan zaman (Felicia Hughes-Freeland, 2008). Dalam praktiknya, ledhek dianggap sebagai perantara roh pelindung yang hadir di tengah komunitas.
Pada saat yang sama, ledhek juga menampilkan hasrat seksual, terutama ketika laki-laki desa menari bergantian dengan perempuan. Dalam hal ini, ledhek dalam tayub dianggap tidak pantas dalam kehidupan sehari-hari menurut norma Orde Baru. Pada masa Orde Baru, tayuban kerap di sensor dengan alasan tidak rasional, boros, pornografis karena interaksi ledhek dengan pengunjung pria (Felicia Hughes-Freeland, 2008). Hal ini bertentangan dengan peran perempuan yang diidealkan negara. Ditambah lagi, definisi resmi mengenai budaya turut mendorong pergeseran makna atas adat semakin jauh.
Definisi adat dan budaya yang dinyatakan negara hanya sebatas budaya material seperti pakaian dan ornamen, sementara itu, budaya non-material hanya mencakup tarian dan lagu. Tata cara dalam mengatur kehidupan sosial serta kepercayaan lokal sama sekali tidak dianggap sebagai adat atau bahkan budaya (Greg Acciaioli, 1985). Budaya didefinisikan hanya sejauh ia dapat dipertunjukkan. Acciaioli menerangkan bahwa karakterisasi semacam ini merupakan indikasi beroperasinya suatu bentuk kekerasan simbolik, yakni pemaksaan narasi resmi yang membatasi budaya.
Dengan demikian, posisi Pancasila sebagai asas tunggal tampak pada perannya mengubah adat menjadi budaya sesuai proyek integrasi nasional Orde Baru. Pancasila diposisikan sebagai filter untuk menentukan adat mana yang layak dipertahankan. Adat yang tidak sesuai moral agama atau ideologi Pancasila digantikan dengan versi yang lebih aman. Setelah desakralisasi berhasil, pertunjukan dengan segala ritual yang menyertainya menjadi hanya sebatas tontonan. Transformasi semacam ini menunjukkan bagaimana Pancasila mengarahkan jalannya perkembangan budaya di tingkat lokal.
Hal tersebut tentunya dapat terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Di Jawa, ada pertunjukan tayub yang mengalami penertiban serupa. Pertunjukan ini mendapat kecaman karena ada aktivitas mabuk-mabukan serta interaksi bebas penari perempuan dengan penonton pria. Akhirnya, pemerintah berupaya menekan aktivitas yang dianggap tidak bermoral dan mengubah tayub menjadi pertunjukan yang lebih pantas dan sopan (Philip Yampolsky, 1995).
Pada akhirnya, Pancasila hadir bukan hanya sebagai kiblat perkembangan budaya, namun juga sebagai batas yang mengontrol ekspresi budaya. Di satu sisi, Pancasila berfungsi sebagai instrumen pemersatu yang menampung keragaman. Namun di sisi lain, ia justru membatasi makna asli budaya yang hadir di tengah masyarakat, seperti ritual pasca panen. Budaya dikonstruksi ulang sesuai nilai agama resmi dan ideologi negara. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya mengarahkan perkembangan budaya, namun ia menetapkan batasan tegas mengenai bentuk, isi, dan ruang gerak budaya itu sendiri.