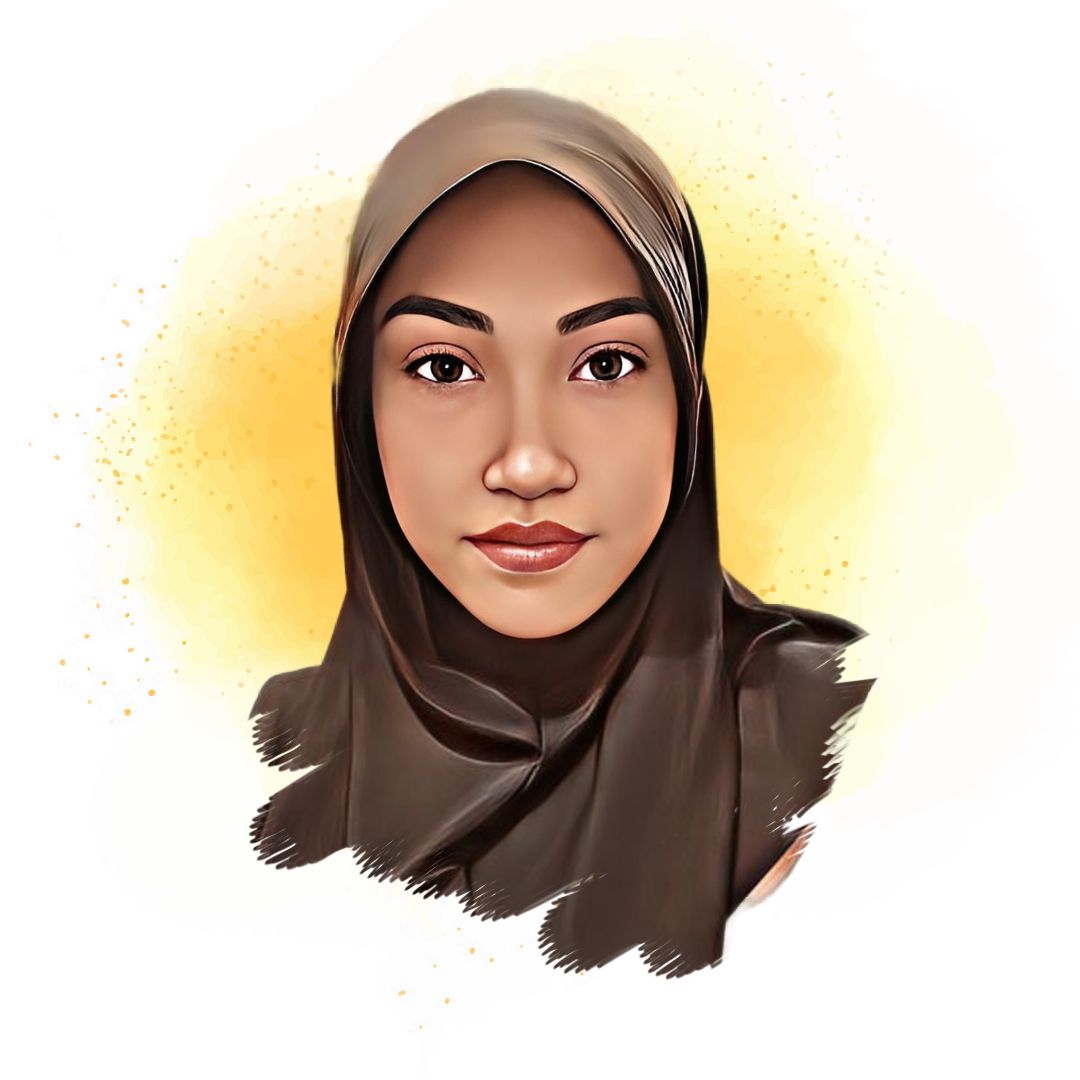Saiful Mustofa bersama dua peneliti Institute for Javanese Islam Research (Seli Muna Ardiani & Khoirul Fata), dalam “Beyond Abangan-Santri: Majelis Sabilu Taubah and New Hybrid Identities” (2025), mengkaji kemunculan identitas hibrida baru di Majelis Sabilu Taubah. Menantang keberlanjutan dikotomi klasik abangan dan santri khususnya di ruang digital. Identitas baru ini terlihat dari panggilan garangan yang diberikan Gus Iqdam kepada jamaahnya. Dimana mereka mengidentifikasi diri sebagai santri namun masih mempertahankan aspek-aspek profesi yang seringkali dinilai melanggar syariat. Dengan cara ini, mereka membangun dan mengekspresikan identitas keagamaannya.
Berangkat dari pengamatan terhadap Majelis Sabilu Taubah, Mustofa menunjukkan bahwa praktik keislaman masyarakat Jawa kontemporer tidak lagi dapat dipahami melalui kategori identitas yang kaku sebagaimana diwariskan oleh tradisi Geertzian. Sebaliknya, ia menampilkan Islam Jawa sebagai medan yang cair dan lentur, tempat identitas keagamaan dinegosiasikan secara terus-menerus. Kelompok garangan menjadi contoh paling menonjol dari proses ini, karena keberadaannya berada di luar jangkauan klasifikasi klasik abangan maupun santri.
Istilah garangan digunakan untuk merujuk pada apa yang oleh Gus Iqdam disebut sebagai “santri mbeling”, yakni jamaah yang berasal dari latar belakang sosial yang secara moral kerap distigmatisasi, seperti penjudi, peminum alkohol, germo, pemandu karaoke, atau individu dengan kondisi sosial serupa. Kategori ini menandai kelompok yang berada di luar representasi ideal kesalehan Islam arus utama, namun tetap terlibat aktif dalam ruang pengajian dan praktik religius.
Meskipun menegaskan afiliasi sebagai santri Gus Iqdam, para garangan tidak sepenuhnya meninggalkan profesi dan praktik hidup tersebut. Mereka menolak label abangan, tetapi juga tidak mengklaim diri sebagai santri dalam pengertian tradisional. Karena itu, garangan tidak dapat dipetakan secara langsung ke dalam tipologi Geertz maupun Ricklefs, dan justru mengungkap keterbatasan kategorisasi klasik dalam membaca dinamika Islam Jawa kontemporer.
Khusus bagi kelompok ini, Gus Iqdam mengembangkan model dakwah yang menekankan Islam sebagai agama yang membumi dan inklusif, tanpa menanggalkan pesan taubat sebagai poros spiritual. Pendekatan ini diperkuat melalui pemanfaatan media sosial sebagai ruang baru, yang memungkinkan Majelis Sabilu Taubah menjangkau audiens lintas wilayah dan latar sosial berbeda. Dakwah tidak hanya berlangsung sebagai transmisi doktrin, melainkan sebagai praktik kultural yang mengafirmasi pengalaman hidup jamaah, termasuk pengalaman yang selama ini dianggap bermasalah.
Secara konseptual, artikel ini sejalan dengan kritik pasca-Geertz yang telah lama disuarakan oleh sejumlah pengkaji wacana Islam Jawa. Namun, keunggulan utamanya terletak pada keberhasilannya memindahkan perdebatan dari tataran konseptual-makro menuju praktik keagamaan sehari-hari dalam ruang pengajian populer. Majelis Sabilu Taubah dipotret bukan sekadar sebagai arena dakwah, melainkan sebagai ruang sosial tempat identitas keislaman dinegosiasikan, dinetralkan, dan dipraktikkan secara inklusif.
Dalam konteks ini, Sabilu Taubah menghadirkan corak Islam yang tidak menuntut pemutusan total dengan masa lalu jamaahnya. Para peserta pengajian khususnya garangan sering kali memiliki latar belakang yang dalam wacana lama akan dikategorikan sebagai abangan. Yang mana digambarkan jauh dari praktik ritual formal dan tidak terikat pada institusi pesantren maupun komunitas Islam manapun. Namun, berbeda dari stereotip Muslim nominal, kelompok ini justru menunjukkan afinitas yang kuat terhadap nilai-nilai kesalehan santri, seperti pengakuan terhadap otoritas kiai, praktik dzikir dan shalawat, serta kesadaran normatif akan kewajiban syariat.
Ambiguitas ini tampak ketika jamaah garangan mengakui kewajiban shalat dan puasa Ramadhan, sembari mengakui ketidakmampuan mereka untuk sepenuhnya meninggalkan praktik yang dianggap bertentangan dengan syariat, seperti perjudian atau konsumsi alkohol. Posisi ambivalen ini menempatkan mereka dalam ruang abu-abu identitas keagamaan, yang dipahami sebagai bentuk hibriditas baru.
Di titik inilah Mustofa menegaskan posisi mereka tidak dapat direduksi sebagai abangan yang belum disantrikan, juga tidak sepenuhnya dapat dimasukkan dalam kategori santri. Mereka menempati wilayah antara, liminal atau sebuah ruang abu-abu, yang memperlihatkan proses hibridisasi identitas keagamaan. Menjadikan identitas ini melampaui klasifikasi lama, dimana kelompok garangan mewakili identitas diaspora yang cair dan berkembang yang menolak kategorisasi tetap
Dalam konteks inilah Mustofa menegaskan bahwa posisi jamaah garangan tidak dapat direduksi sebagai abangan yang belum disantrikan, sekaligus tidak sepenuhnya dapat dimasukkan ke dalam kategori santri dalam pengertian tradisional. Mereka menempati wilayah antara yang bersifat liminal, sebuah ruang sosial-keagamaan yang memperlihatkan berlangsungnya proses hibridisasi identitas keagamaan. Keberadaan ruang antara ini menunjukkan keterbatasan klasifikasi klasik dalam membaca dinamika Islam Jawa kontemporer.
Lebih lanjut, kesalehan garangan tidak diekspresikan melalui kepatuhan formalistik terhadap hukum Islam, melainkan melalui pengalaman religius yang emosional, reflektif, dan personal. Pola ini menunjukkan bagaimana Islam Jawa bekerja secara lentur, menyesuaikan diri dengan kebutuhan psikologis dan sosial masyarakat. Identitas ini melampaui klasifikasi lama dalam mengkaji Islam Jawa. Sebaliknya, kelompok garangan mewakili identitas diaspora masyarakat yang cair dan berkembang yang menolak kategorisasi tetap.
Temuan ini lagi-lagi memperkuat argumen Masdar Hilmy (2018), yang menyatakan bahwa Islam Jawa tidak lagi dapat dipahami sebagai sinkretis maupun normatif semata. Hilmy menekankan bahwa identitas Islam Jawa telah mengalami transformasi melalui proses Islamisasi dan akulturasi yang berjalan simultan, melahirkan bentuk identitas baru yang hibrid. Namun, berbeda dari Hilmy yang bekerja pada level konseptual dan historis, Mustofa memperlihatkan bagaimana hibriditas tersebut hidup dalam praktik keagamaan konkret.
Lebih jauh, jika Akhmad Rizqon Khamami (2022) menunjukkan pertautan identitas keagamaan dan kebangsaan pada Muslim Jawa nominal. Maka melalui Sabilu Taubah dapat diperlihatkan bagaimana kesalehan Islam dapat tumbuh tanpa harus melalui jalur ideologisasi organisasi atau politik identitas. Kesamaan keduanya terletak pada penolakan terhadap identitas tunggal dan pada pengakuan bahwa Muslim Jawa membangun keberagamaannya melalui berbagai lapisan pengalaman sosial masyarakat.
Namun, Mustofa melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa identitas hibrid tidak selalu berwujud dalam afiliasi formal atau kesadaran ideologis. Pada jamaah Sabilu Taubah, identitas hibrid justru terartikulasikan melalui tangisan taubat, solidaritas emosional, bahasa dakwah yang membumi, serta penerimaan terhadap latar belakang bermasalah jamaah. Inklusivitas inilah yang membuat majelis ini menjadi ruang aman bagi mereka yang secara sosial maupun religius berada di pinggiran.
Dari sudut pandang kajian Islam Jawa, Mustofa bersama dua periset IJIR, secara implisit mengoreksi anggapan bahwa Islamisasi selalu berujung pada penyeragaman praktik dan identitas. Sebaliknya, Sabilu Taubah menunjukkan bahwa proses pendalaman religius justru dapat memperluas spektrum ekspresi keislaman. Islam tampil bukan sebagai sistem normatif yang memaksa, tetapi sebagai etos yang memberi ruang bagi negosiasi identitas.
Dengan demikian, kategori garangan ini penting dibaca sebagai subjek sosial baru dalam Islam Jawa kontemporer. Mereka bukan residu dari abangan, bukan pula santri yang gagal, melainkan produk dari pertemuan antara budaya populer, pengalaman hidup marginal, dan dakwah Islam yang adaptif. Posisi mereka yang di luar abangan dan santri menegaskan bahwa dikotomi klasik tersebut tidak lagi memadai untuk membaca realitas keislaman dewasa ini.
Secara keseluruhan, Beyond Abangan-Santri memperkaya khazanah kajian Islam Jawa dengan menawarkan lensa baru untuk memahami identitas keagamaan di era modern. Ia menegaskan bahwa Islam Jawa bukan entitas statis, melainkan ruang hidup yang terus membentuk dan dibentuk oleh pengalaman sosial umatnya. Dalam konteks ini, Majelis Ta’lim Sabilu Taubah menjadi contoh konkret bagaimana hibriditas bukan anomali, melainkan bentuk keberagamaan yang nyata, luwes dan inklusif.