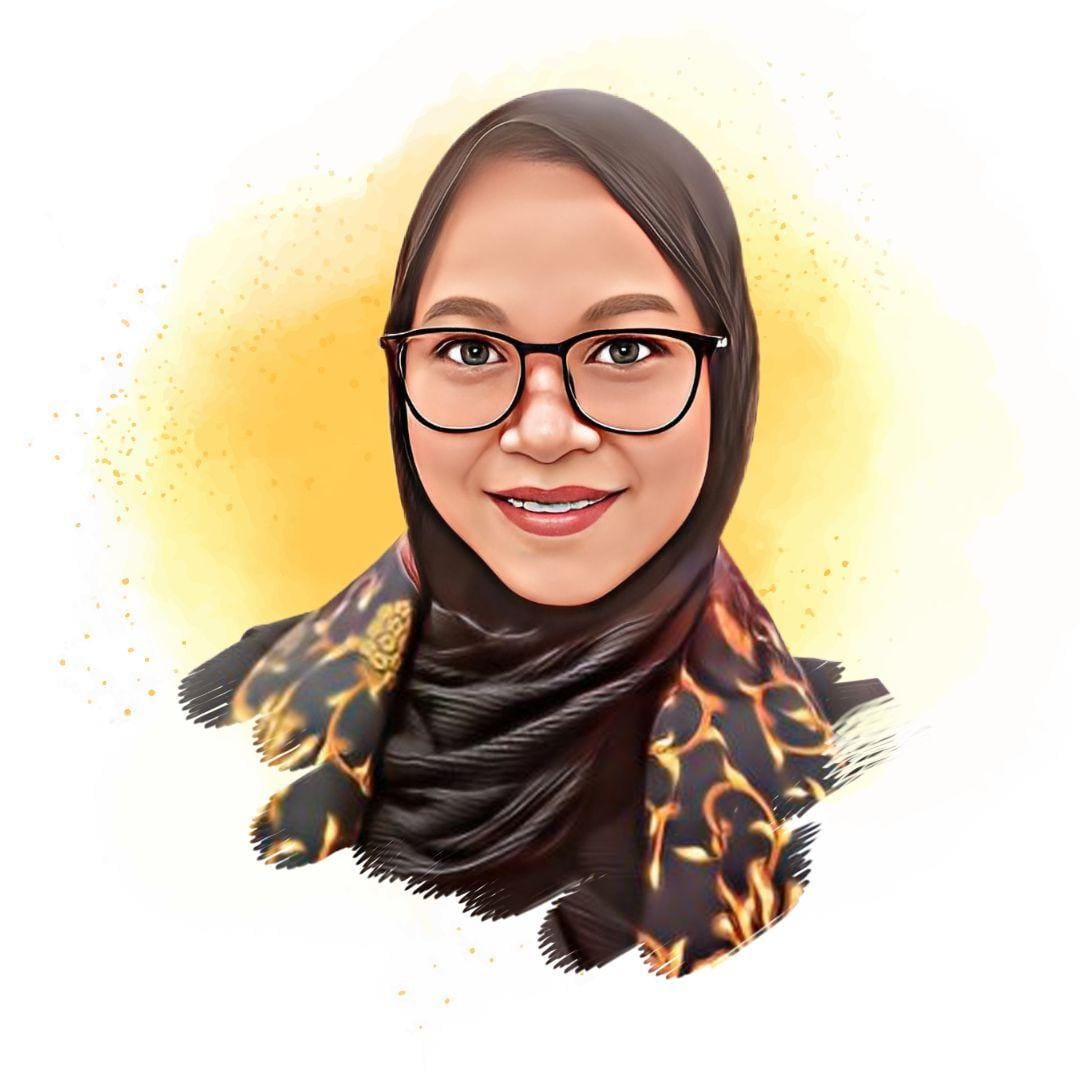Negara berkembang menghadapi tantangan lebih rumit dibanding negara maju dalam pembangunan ekonomi pasca perang. Lebih dari itu, menerapkan model “proses ekonomi” yang digunakan di negara maju seringkali tidak relevan dengan realitas di negara berkembang. Untuk memahami dan mengatasi kesenjangan ini, beberapa ekonom seperti J.H. Boeke menawarkan teori dualisme sosial-ekonomi sebagai upaya menjelaskan dinamika dan tantangan yang dihadapi.
Namun, teori Boeke tidak luput dari kritik. Akademisi seperti D.H. Burger dan Benjamin Higgins menilai bahwa pendekatan ini mengabaikan konteks pascakolonial, tidak menawarkan solusi konkret, dan terlalu statis dalam memahami dinamika perubahan sosial-ekonomi di kawasan negara berkembang. Mereka menekankan bahwa dalam proses bertransisi, negara-negara berkembang menghadapi realitas yang lebih kompleks, sehingga perubahan ekonomi tidak bisa dipandang sebagai dualisme yang kaku.
Yoichi Itagaki membingkai perdebatan tersebut dalam karyanya berjudul “Some Notes on The Controversy Concerning Boeke’s ‘Dualistic Theory’: Implications for The Theory of Economic Development in Underdeveloped Countries” . Karya ini diterbitkan dalam Hitotsubashi Journal of Economics, Vol. 1, No. 1 (October 1960), halaman 13-28 (16 halaman). Jurnal ini diterbitkan oleh Hitotsubashi University, salah satu institusi akademik terkemuka di Jepang yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang ekonomi dan ilmu sosial.
Struktur Teori Dualisme Boeke
Inti dari teori Boeke adalah gagasannya tentang dualisme sebagai pendekatan khusus untuk memahami karakteristik sosial dan ekonomi di Asia Tenggara. Awalnya, teori dualismenya disebut sebagai Tropisch-Koloniale Staathuishoudkunde (Ekonomi Negara Tropis-Kolonial), kemudian berkembang menjadi Oosterse Economie (Ekonomi Timur). Teori ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa ekonomi di kawasan tersebut cenderung mengalami stagnasi, bahkan kemunduran serta mengapa pola pembangunan di negara berkembang tidak dapat disamakan dengan negara maju.
Menurut Boeke, masyarakat di kawasan Asia Tenggara—khususnya Indonesia, yang ia jadikan sampel—memiliki dua sistem berbeda, yakni sistem modern dan tradisional, masing-masing terepresentasi dalam kota dan desa. Kedua sistem tersebut eksis secara bersamaan, membentuk apa yang disebut sebagai “masyarakat dualistik.” Dalam struktur ini, sistem asli masyarakat tetap bertahan di tengah arus perubahan yang dibawa oleh sistem baru. Namun, keduanya berkembang secara terpisah karena tidak ada proses transisi yang jelas dari satu sistem ke sistem lainnya.
Seperti dalam amatannya terhadap desa di Indonesia, desa tidak hanya sekedar tempat tinggal fisik melainkan juga sebagai suatu organisme hidup (living organism). Anggota masyarakat desa umumnya saling terhubung melalui ikatan sosial yang kuat. Aktivitas mereka lebih didorong oleh kepentingan bersama daripada keinginan pribadi. Selain itu, agama dan spiritualitas memainkan peran sentral dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan spiritual ini bahkan menjadi pembentuk identitas dan kesatuan sosial dalam komunitas.
Terlebih, desa juga memiliki sistem pertukaran ekonomi mereka sendiri. Tanah, misalnya, merupakan faktor produksi utama ekonomi desa. Akibatnya, apabila terjadi pembagian tanah, lahan pertanian menjadi sangat terbatas. Selain itu, peredaran uang di desa lebih berfungsi sebagai alat pertukaran lokal (money traffic), alih-alih sebagai alat akumulasi modal. Pasar desa pun lebih berfungsi sebagai tempat interaksi sosial daripada sebagai lembaga ekonomi. Jika disederhanakan, pola ekonominya cenderung bersifat subsisten, dengan produksi lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar daripada untuk mencari profit seperti pasar global.
Sementara itu, wajah modernitas kota cenderung sebatas sebagai pusat kekuasaan pemerintahan dan konsumsi. Selain berfungsi sebagai pemungut pajak, kota tidak memiliki interaksi ekonomi yang saling menguntungkan dengan desa-desa. Kota lebih banyak mengeksploitasi desa sebagai sumber pendapatan, tanpa memberikan manfaat yang setara bagi perkembangan ekonomi pedesaan. Akibatnya, desa tetap terisolasi dalam sistem ekonomi tradisional, dengan akses terbatas terhadap teknologi, infrastruktur, dan berbagai barang industri yang dapat meningkatkan produktivitas. Kota, yang seharusnya berperan sebagai pusat distribusi dan inovasi justru memperkuat kesenjangan dengan desa.
Dengan kata lain, kedatangan sistem kapitalisme Barat atau sosial impor (Imported Social System) telah menindas sistem Sosial Asli (Indigenous Social System) yang bersifat agraris dengan struktur ekonomi pra-kapitalistik untuk memenuhi keuntungan produksi pasar global. Perbedaan mendasar ini menciptakan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan modern yang sulit untuk disatukan dalam satu sistem ekonomi yang harmonis. Berbeda dengan masyarakat homogen yang mengalami perubahan sosial secara bertahap, masyarakat yang mengalami dualisme ini terjebak dalam ketidakseimbangan antara dua sistem yang saling bertentangan, tanpa ada integrasi yang jelas di antara keduanya.
Kritik Para Ahli
Seperti yang telah saya singgung sebelumnya, teori Boeke mendapat kritik dari beberapa ahli. Salah satu kritik datang dari Burger, yang menilai bahwa Boeke keliru dalam menafsirkan konsep pra-kapitalisme milik Sombart. Menurut Burger, Sombart tidak memandang pra-kapitalisme sebagai sebuah sistem yang tetap, melainkan sebagai suatu periode dalam perkembangan ekonomi. Di sisi lain, Higgins menolak klaim Boeke yang menyatakan bahwa dualisme merupakan fenomena khas Timur. Menurutnya, dualisme tidak hanya terbatas pada masyarakat di Asia, tetapi juga dapat ditemukan di Barat. Ia berargumen bahwa dualisme seharusnya dipahami sebagai suatu spektrum kontinu, bukan sebagai pemisahan yang kaku antara sistem tradisional dan modern.
Sebenarnya, masih banyak kritik yang dilontarkan oleh kedua ahli tersebut, namun yang paling mendasar adalah kritik mereka terhadap Boeke yang gagal melihat masyarakat dualistiknya dalam konteks kolonialisme. Meskipun dalam teorinya, Tropisch-Koloniale Staathuishoudkunde (Ekonomi Politik Kolonial Tropis), Boeke menggunakan istilah “kolonial” (koloniale), istilah ini tidak menunjukkan bahwa ia secara eksplisit memperhitungkan kolonialisme sebagai faktor utama yang membentuk dualisme sosial-ekonomi.
Masih menurut Higgins, Boeke tampaknya lebih fokus pada deskripsi dualisme sebagai fenomena yang bersifat internal dalam masyarakat dan karakteristiknya muncul secara alami dalam struktur sosial-ekonomi masyarakat. Ia lebih menekankan pada perbedaan antara sistem tradisional dan modern yang ada di dalam masyarakat, tanpa cukup memperhitungkan pengaruh eksternal, seperti kolonialisme, yang berperan penting dalam menciptakan dan memperdalam dualisme ini. Dengan pandangannya, Boeke cenderung melihat dualisme sebagai sesuatu yang melekat dalam dinamika sosial, padahal banyak aspek sosial-ekonomi yang sebenarnya dipengaruhi oleh struktur kolonial yang mengatur hubungan antara desa dan kota, serta antara tradisi dan modernitas.
Pandangan yang kurang mempertimbangkan faktor eksternal ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai pendekatan yang tepat dalam memahami dan mengatasi tantangan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Selain sependapat dengan para ahli yang mempertanyakan mengapa Boeke mengabaikan konteks kolonial, saya juga berpikir bahwa ada persoalan mendasar yang perlu dibahas lebih lanjut: bagaimana sebaiknya solusi yang tepat bagi negara berkembang yang tidak hanya menghadapi tantangan ekonomi, tetapi juga persoalan sosial yang kompleks? Bagaimana negara dapat memainkan peran sebagai kekuatan pendorong awal dalam pembangunan tanpa terjebak dalam dominasi struktural yang justru memperkuat ketimpangan?
Dalam konteks ini, penting untuk terus mengkritisi teori-teori pembangunan yang ada, sekaligus mencari pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan agar pembangunan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga membawa perubahan nyata bagi masyarakat luas. []